Biasanya
Rajwa, anak perempuanku yang menyapu
laintai berkeramik putih gading ini. Belum genap sebulan ia diboyong suaminya
ke Kalimantan. Aku seorang ibu yang baru saja belajar melepaskan anak perempuan
satu-satunya ke tempat yang jauh pada orang yang baru dikenalnya. Namun,
pernikahan telah menjadi nasihat, bahwa syurga Rajwa bukan lagi di bawah
naungan keridaanku. Namun, ada pada suaminya, Fahda. Setelah akad nikahnya pun,
bukan kami sebagai orang tua yang ia mohonkan restu, tetapi suaminya. Aku belum
benar-benar rela, bahwa melepaskan darah dagingku sendiri, butuh masa yang tidak
sederhana. Suamiku yang terlihat legowopun aku pernah memergokinya mengusap
bulir bening dari matanya, kala memandang fhoto pernikahan Rajwa.
Hari
ini, aku masih duduk di anak tangga belakang rumah. Menatap hiruk-pikuknya
hewan ternak peliharaan keluarga kami. Suara nyaring bebek jantan memenuhi
setiap jengkal rongga pendengaran. Di tangga ini aku menghabiskan waktu sore
selepas memasak. Tidak jarang aku menangis tersedu, mengingat Rajwa, anakku,
kala suamiku tidak ada di rumah. Deritan bamboo berwarna hijau kehitaman
beberapa meter di hadapanku, mampu melemparku jauh pada kenangan keberadaan
Rajwa sebelum pernikahannya. Di sekitaran bambu itu, ia sering menghabiskan
harinya, meski itu sekedar membaca buku kesukaannya. Melihat batang bamboo meliuk-liuk diterpa angin,
mataku panas. Ada yang benar-benar kurindukan tentang keberadaan putriku.
“Bu
… coba tebak Bapak bawa apa?” Tiba-tiba Mas Lukman menghampiriku. Tampak ia memeluk
bayi kucing. Bulunya lebat dan halus. Mataku membulat menatapnya. Baru kali ini
secara langsung aku bertemu dengan kucing secantik ini. Sejurus kemudian,
kucing yang konon kata majikan sebelumnya berumur empat bulan itu, sudah ada di
pelukanku.
“Bu
….” Suamiku memanggil, aku tahu dari tadi ia menatapku.
“Dalem
….” Aku masih mengelus bulu kucing berwarna abu-abu di pangkuan.
“Nggak
usah sedih lagi, memiliki anak perempuan memang harus siap melepas dibawa
kemanapun oleh suaminya. Sama halnya, ketika sampean saya boyong ke luar dari
Solo, dan kita tinggal di Lampung saat ini. Tidak ada di dunia ini yang pantas
kita cintai berlebihan.” Aku
hanya diam, kepalaku tertunduk kian dalam. Anak kucing yang telah terpisah
dengan induknya ini mulai basah oleh air mataku.
“Ibu,
masih ingat kisah Nusaibah binti Ka’ab, bukan? Ia seorang sahabiyah Rasulullah
yang mendapat gelar Perisai Rasulullah. Seorang perempuan yang merelakan dengan
hati terbaiknya ditinggal oleh suami berikut anaknya. Perpisahan mereka bukan
hanya perpisahan dunia. Tetapi, perpisahan mereka adalah perpisahan kematian,
dua dunia berbeda. Suami dan anaknya gugur di medan perang, dan ia rela akan
takdirnya,ia meyakini bahwa kematian suami dan putranya adalah dalam membela
agama Allah. Ia mengabdikan hidupnya untuk turut ke medan perang menjadi tim logistik
dan medis, untuk prajurit yang terluka.” Aku masih mendengarnya dengan
sesenggukkan. Sudah tidak bisa lagi kusembunyikan bulir air mata ini.
“Ibu
yang rida, biarkan Rajwa memulai dan melanjutkan ibadah pernikahannya. Rajwa
masih bisa menemui kita, atau kita yang mengunjunginya. Bapak berharap, Ibu
kuat menghadapinya sekuat Nusaibah menerima takdirnya. Jika Nusaibah binti Ka’ab
mendapat gelar Perisai Rasulullah, karena mengabdikan umurnya untuk untuk sosok
mulia Nabi Muhammad di medan perang sedari serangan musuh, ia tercatat menderita
dua belas luka demi menjadi perisai Rasulullah dalam perang uhud.” Ia mencoba
menatap manik mataku.
“ Bapak berharap, Ibu bisa menjadi perisai untuk Rajwa karena
merelakannya dan menjadi jalan ia berbakti pada suaminya, dan balasannya
insyaAllah syurga.” Jemari Mas Lukman perlahan menepuk pundakku yang mulai
terguncang hebat. Aku malu, bagaimana aku serapuh ini menjadi ibu. Akulah contoh
nyata dari ungkapan ‘mati sajroning urip’ meski aku hidup, namun aku tidak
memiliki semangat atau gairah dalam menjalani kehidupan.
Nasihat
suamiku sebisa mungkin aku terima dan melaksanakannya. Kini aku menjadi sosok
ibu untuk kucing yang kian hari bertumbuh. Setiap pagi aku menyeduhkannya susu
dan meletakkan makanannya dalam piring. Bulunya kian memanjang, matanya hitam
kecoklatan penuh kilat memesona.
“Boboy
… Boboy ….” Kupanggil kucing berbulu panjang itu, ia merupakan perpaduan kucing
kampung dan Persia. Ia melompat girang menujuku. Memutariku berkali-kali. Sore ini
kegiatanku memberi makan untuk aneka hewan ternak di kandang bawah. Boboy tampak
duduk menghadap arah timur, lurus dengan kandang belakang rumah. Ia menungguku
di atas anak tangga. Suasana ini sangat membuatku kembali bersemangat dan
hidup. Ketika azan magrib mulai berkumandang. Aku menuju padasan samping rumah,
musala yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumah itu hanya perlu ditempuh
menggunakan beberapa langkah kaki. Boboy sudah turun dari anak tangga. Menujuku,
dan berada tidak jauh dari aku mengambil air suci. Ketika aku menuju musala,
kucing berbulu panjang itu kembali membuntutiku dan sesekali mensejajarkan langkah
denganku. Kunikmati suasana ini setiap harinya, hingga keadaan menamparku memberi
nasihat, jangan cintai dunia seluruhnya.
“Boboy
….” Panggilan yang sudah kugaungkan berpuluh-puluh kali, tidak berhasil membawa
Boboy padaku. Kususuri setiap sudut rumah, tidak kutemui ia di sana. Hatiku berdegup
kencang setiap langkahku terus bergerak maju. Aku berulang kali merutuki diri,
kenapa rumah tidak kukunci ketika membeli sayuran di warung. Mataku mulai
panas, bayangan anakku berwujud kucing itu kembali berkelebat. Ia bukan hanya
hewan peliharaan bagiku, namun juga teman dan sosok anak yang kembali
menghidupkan rumah ini.
“Udah,
Bu. Sabar nggak usah nangis lagi, jika rizkinya pasti kembali dan kita temukan,”
pintanya kemudian, karena ia menemukan aku mulai menangis. Bukannya tangisku
berhenti, justru air mataku kian deras. Aku berlari menuju pohon bambu, dimana
Boboy juga sering menghibur diri dengan memainkan dedaunan yang berguguran. Lagi-lagi
tidak kutemukan ia di sana. Kantung mataku kian menggelembung. Lututku mulai
ngilu. Aku duduk di atas dedaunan bambu.
“Ibu
tahu mengapa Rajwa senang sekali berada di sekitaran rumput bambu ini?”
Aku
hanya menggeleng, aku hanya membatin mengapa Mas Lukman menyebutnya rumput. Aku
sedang enggan menanggapinya.
“Bambusea
adalah nama latin dari bambu yang masuk dalam kategori keluarga rumput yang
memiliki rongga dan ruas pada batangnya. Bambu juga tergolong tanaman yang memiliki pertumbuhan tercepat di dunia, Bu. Bagi
orang Tiongkok, bambu dijadikan simbol kekuatan dan keteguhan. Bambu juga
sering dijadikan simbol kstaria dan keberanian, proses pencapaian kemerdekaan bangsa
kita juga tentu tidak terpisahkan dengan salah satu senjata tradisional dari bambu
untuk melawan penjajah. ” Ia menjelaskan tanpa kupinta.
“Bapak
pernah menceritakan kisah ini pada Rajwa,” imbuhnya kemudian.
“Bu,
ada falsafah jawa tentang bambu, yakni ‘Pring
dheling tegese kendhel lan eling, kendhel mergo eling timbang grundel nganti
suwing’ ungkapan ini memiliki
arti bahwa orang hidup haruslah tahu dengan dirinya dan selalu mawas diri,
jangan selalu menggerutu dalam menjalani kehidupan. Ada banyak hal tidak
terduga setelah ini, Bu. Jangan sampai Ibu menyalahkan Tuhan sebagai sebab atas
kesedihan yang kita terima.” Air mataku menyembul kembali ketika mendengar
kalimat demi kalimat yang meluncur dari mulut suamiku.
“Hidup ini selalu dipenuhi masalah, Bu. Masalah
selalu membuat kita kesepian dan bersedih bahkan bingung menjalaninya. Meski demikian
semoga kita senantiasa kuat, jangan sampai kita bingung menghadapinya,
setidaknya itulah hal yang bisa kita lakukan dari petuah jawa, 'pring
petung, urip iku suwung senajan suwung nanging ojo podo nganti bingung.” Ia menerawang jauh, aku tidak
tahu pasti apayang ia pikirkan. Berikutnya, ia berpamitan padaku, lalu
membiarkan aku menenangkan diri dan memahami perlahan apa yang ia sampaikan. Wajah
Rajwa yang ceria memelukku, tingkah lucu dan wajah manis Boboy menghampiri
benakku. ‘Aku akan belajar merelakanmu, anak-anakku,’ bisikku dalam hati, dan
air mataku telah menganak sungai sedari tadi.
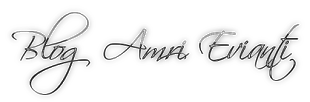





Harus setegar itu jadi sosok "Ibu" di cerpen ini. Setelah ditinggal sang anak perempuan satu-satunya menikah dan ikut suaminya, kini sang kucing kesayangan juga menghilang :(
ReplyDeleteWah, udah jarang banget kayaknya yang mengenal istilah "padasan" sekarang ini mbak? Itu istilah dari orang Jawa bukan ya?